Oleh: Muhammad Hanif – Founder Swara Pemoeda
KUNINGAN, (VOX) – Selasa, 23 Desember, air kembali mengingatkan kita bahwa ia tidak pernah lupa jalan pulang. Beberapa titik di Cirebon dan Kuningan terendam banjir. Bukan banjir besar yang langsung menelan ratusan korban, memang. Tapi sejarah bencana selalu bekerja dengan cara yang sama. Ia datang pelan pelan, lalu tiba tiba. Pertanyaannya bukan lagi apakah banjir akan terjadi, melainkan apakah kita masih mau pura pura kaget ketika banjir bandang benar benar datang.
Selama ini Gunung Ciremai diperlakukan seperti etalase. Indah dilihat, tapi dianggap boleh dipreteli bagian belakangnya. Lereng dibuka, vegetasi ditebang, kontur tanah diubah, semuanya atas nama investasi, pariwisata, dan penggerak ekonomi daerah. Narasinya selalu terdengar manis. Lapangan kerja, peningkatan PAD, dan kemajuan daerah. Namun ilmu lingkungan tidak bekerja dengan narasi. Ia bekerja dengan hukum sebab akibat. Dan hukumnya sederhana. Ketika hutan di hulu dilemahkan, air di hilir akan mencari jalan sendiri.
Data menunjukkan bahwa dalam periode 2021 hingga 2024, Kuningan kehilangan sekitar 140 hektare hutan alam. Sebagian berada di wilayah sensitif lereng dan hulu daerah aliran sungai. Angka ini mungkin tampak kecil bagi meja rapat investor, tapi sangat besar bagi tanah yang harus menahan hujan, akar yang seharusnya memegang lereng, dan mata air yang menjadi tumpuan hidup warga.
Banjir yang terjadi pada 23 Desember kemarin seharusnya tidak dibaca sebagai peristiwa terpisah. Ia adalah gejala, bukan anomali. Dalam kajian hidrologi, banjir lokal yang berulang menandakan tiga hal. Daya serap tanah menurun. Tutupan vegetasi melemah. Aliran permukaan meningkat lebih cepat dari kapasitas sungai dan drainase. Dengan kata lain, air tidak lagi disambut tanah, tapi diusir.
Ironisnya, peristiwa ini terjadi ketika wacana pembukaan dan pemanfaatan lereng Ciremai justru semakin agresif. Seolah kita sedang berdiskusi soal dekorasi rumah, sementara pondasinya mulai retak.
Banjir bandang di Sumatra yang dipicu kombinasi hujan ekstrem dan deforestasi hulu sudah memberikan studi kasus yang sangat mahal. Lebih dari 4,4 juta hektare hutan hilang sejak 2001. Dampaknya bukan hanya banjir, tapi tsunami kayu, longsor, dan desa yang lenyap dalam hitungan menit. Secara akademis, kesimpulannya tegas. Tidak ada banjir bandang tanpa kerusakan hutan di hulu. Secara moral, pesannya lebih sederhana. Alam tidak pernah berdamai dengan pembiaran.
Ironisnya, masyarakat Sunda sejak lama sudah memiliki kerangka ekologis yang jauh lebih maju dari banyak dokumen AMDAL hari ini. Konsep hutan larangan, hutan tutupan, dan hutan baladahan bukan sekadar tradisi, melainkan sistem mitigasi bencana berbasis pengalaman lintas generasi. Hutan larangan tidak boleh disentuh. Hutan tutupan boleh dimanfaatkan terbatas dengan syarat tutupan tetap utuh. Hutan baladahan adalah ruang kelola masyarakat, bukan ruang eksploitasi korporasi.
Lereng Ciremai bagian atas, baik dalam kacamata adat Sunda maupun ilmu lingkungan modern, jelas masuk kategori hutan larangan. Membukanya bukan inovasi. Itu kemunduran.
Setiap kali kritik menguat, pola responsnya hampir selalu sama. Klarifikasi, konferensi pers, penanaman pohon simbolik, lalu janji bahwa semuanya sesuai prosedur. Masalahnya, bencana tidak membaca siaran pers. Akar pohon yang baru ditanam hari ini tidak akan menahan longsor besok pagi. Hutan membutuhkan puluhan tahun untuk berfungsi, sementara satu alat berat bisa merusak ekosistem dalam satu sore. Pertanyaannya sah dan rasional. Jika bisa menjaga, kenapa harus membabat.
Hari ini Kuningan berdiri di persimpangan yang jelas. Jalan pertama adalah pembangunan instan yang menggerus lereng, menggadaikan hulu, dan menunda bencana. Jalan kedua adalah pembangunan berbasis daya dukung lingkungan, hukum, dan kearifan lokal.
Banjir 23 Desember kemarin adalah catatan kaki dari masa depan yang sedang kita tulis sendiri. Ia belum menjadi tragedi besar, dan justru karena itu masih ada waktu untuk berhenti.
Karena sejarah bencana selalu kejam pada satu hal. Ia tidak pernah peduli apakah manusia sudah diperingatkan atau belum. Dan jika suatu hari Kuningan benar benar dilanda banjir bandang, pertanyaan terpenting bukan lagi siapa yang salah, melainkan mengapa kita memilih diam ketika air sudah mulai naik.***














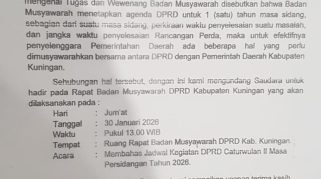




Tinggalkan Balasan